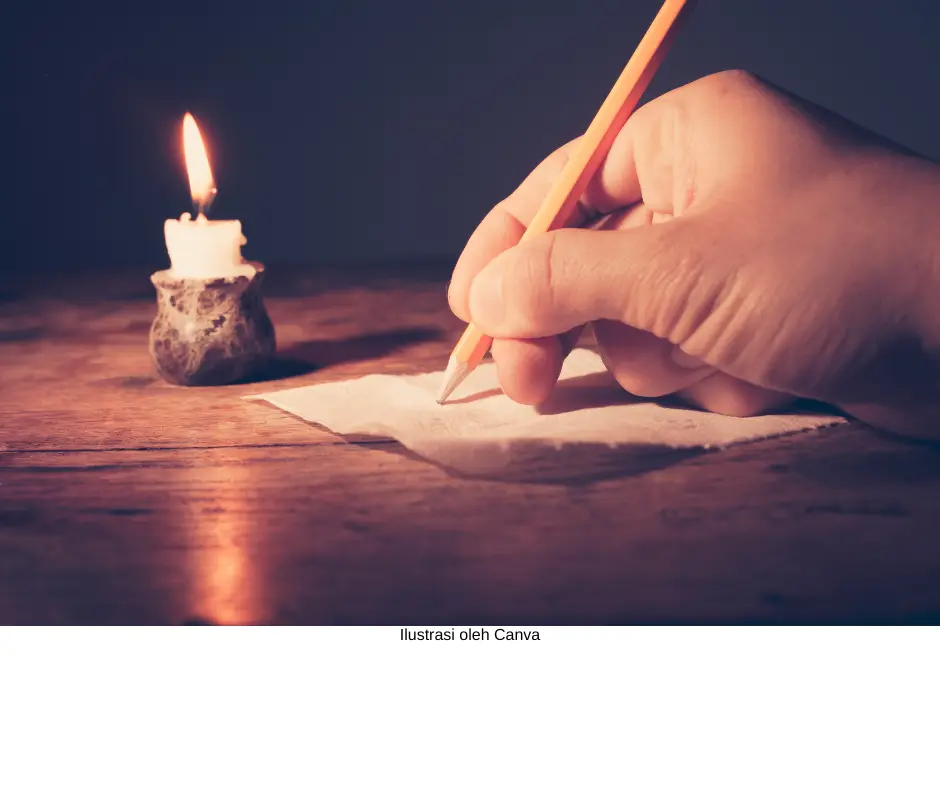Aku tak bermaksud mewakili apapun selain diriku sendiri.
Tapi diriku dipenuhi oleh memori kolektif.
[Mahmoud Darwish]
Ketika Mahmoud Darwish dimakamkan di Ramallah Cultural Palace pada Agustus 2008, puluhan ribu orang Palestina berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir kepada sang penyair di Tepi Barat. Presiden Mahmoud Abbas memimpin langsung pemakaman tersebut. Dengan peti mati berbalut bendera Palestina, diiringi dengan 21 tembakan salut, Mahmoud Darwish menjadi orang kedua yang dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Palestina. Orang sebelumnya yang mendapat penghormatan serupa adalah Yasser Arafat, Presiden Palestina pertama.
Agak sulit, memang, membayangkan bagaimana seorang penyair yang bermodalkan kata-kata bisa menjadi pahlawan nasional bagi suatu bangsa, terlebih-lebih di abad ke-21 yang tak henti-henti disupersibukkan oleh perkembangan teknologi yang kian canggih. Mahmoud Darwish benar-benar adalah penyair tulen. Ia bukan penyair yang juga sekaligus diplomat seperti Nizar Qabbani atau Pablo Neruda; bukan penyair yang juga sekaligus prajurit militer seperti Dante Alighieri; atau penyair “yang-juga-sekaligus” lainnya. Meski begitu, tanpa diplomasi, Mahmoud Darwish ikut mengumandangkan riwayat Palestina ke seluruh dunia dengan amat apik; tanpa bedil dan granat, ia ikut memerangi para penjajah yang merobek-robek negeri Palestina selama hayat dikandung badan. Semua itu dilakukan Darwish dengan kata-kata‒melalui puisi.
Mahmoud Darwish jelas heroik, dan ia kerap menjadi contoh nyata betapa puisi bisa menjadi alat perjuangan bagi sebuah bangsa yang ingin merdeka dan berdaulat. Meski begitu, kita tak boleh buru-buru melihat hubungan puisi dan hal ihwal kebangsaan sesederhana itu saja. Puisi tak harus melulu bicara soal bangsa untuk menyumbangkan peran signifikannya bagi kebaikan suatu bangsa. Kita akan mencoba melangkah lebih jauh.
#
Hubungan puisi dan kebangsaan dapat dilihat paling gamblang pada zaman romantik (abad ke-19) di Eropa. Pada zaman itu di Eropa (kemudian menyebar ke belahan dunia lainnya) mulai berkembang gagasan tentang nasionalisme, dan sejumlah masyarakat mengidentifikasi diri mereka sebagai bangsa-bangsa yang memiliki karakter khas. Karena konsep karakter bangsa ini bersifat sangat abstrak, maka ia dianggap menemukan bentuk konkretnya, atau manifestasinya dalam sejumlah ekspresi kebudayaan, terutama karya seni, terlebih lagi sastra. Maka, pada zaman ini penyair menempati posisi sangat penting bagi bangsanya. Ia dianggap sebagai representasi kunci bagi roh/kesadaran bangsanya.
Dalam bayang-bayang semangat romantik yang sama, Bapak Spiritual Pakistan, Muhammad Iqbal (1877‒1938) kemudian berkata, “Bangsa lahir di hati para penyair, ia makmur dan mati di tangan para politisi.”
Di Indonesia, peran penyair bagi eksistensi bangsa seperti yang dikemukakan Iqbal tampak relatif kompleks. Meski manusia-manusia Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun lampau, tapi identitas bangsa Indonesia sebagai kesatuan beragam suku bangsa baru muncul atau ditegaskan pada 1928 melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Itu peristiwa sangat penting bagi kelangsungan bangsa Indonesia selanjutnya, dan salah satu tokoh pentingnya, jika bukan kunci utama, yaitu Muhammad Yamin. Yamin kini lebih dikenal sebagai negarawan-politisi yang pernah menjadi sejumlah menteri di masa Orde Lama. Namun, pada mulanya Yamin adalah seorang penyair yang berperan memperkenalkan bentuk soneta dalam tradisi sastra Indonesia. Ia adalah pembaharu puisi modern Indonesia. Tema-tema karyanya pun banyak berkisar seputar nasionalisme dan persatuan. Frasa-frasa seperti ‘tanah air’, ‘tumpah darahku’ merupakan ungkapan yang lahir dan populer melalui karya-karya puisinya. Ia mendahului lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman sangat mungkin terinspirasi oleh puisi-puisi Yamin. Atau, seperti keterangan sejumlah pihak, termasuk budayawan A.A. Navis dan sejarawan senior Taufik Abdullah yang dikutip Tempo dalam buku Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuji, Yamin sebenarnya adalah penulis lirik lagu kebangsaan Indonesia itu sendiri. (Sejumlah lagu kebangsaan negara-negara di seluruh dunia juga ditulis oleh penyair-penyair besar. Bahkan, lagu kebangsaan India dan Bangladesh ditulis oleh satu penyair peraih Nobel Sastra 1913, Rabindranath Tagore.)
Kesadaran Yamin terkait pentingnya bahasa Melayu/Indonesia bagi persatuan dan eksistensi bangsa Indonesia tidak hanya ia implementasikan melalui Sumpah Pemuda, tapi juga melalui aktivitas menulis dalam bahasa Melayu secara rajin. Masa itu intelektual-intelektual pribumi banyak menulis dalam bahasa Belanda, sementara Yamin banyak menulis dalam bahasa Melayu, bahkan di jurnal berbahasa Belanda. Ia terus menulis dalam bahasa Melayu pada masa-masa seterusnya. Alhasil, ia melahirkan banyak tulisan, mulai dari kumpulan puisi, naskah drama, hingga buku-buku politik dan sejarah‒semua dalam bahasa Melayu/Indonesia. Ia bahkan juga menerjemahkan ke bahasa Melayu/Indonesia karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore. Ia pernah menulis, “Apabila perasaan baru sudah mendirikan pustaka baru dalam bahasa tumpah daerah kita, maka lahirlah zaman yang mulia, sebagai pertandaan peradaban baru, yaitu peradaban Indonesia-Raya.”
Yamin jelas menyadari perlunya tradisi sastra Indonesia yang besar bagi alam pikiran bangsa Indonesia yang hebat ke depannya. Manusia-manusia Indonesia memang tidak asing dengan sastra sejak beratus-ratus tahun lampau, tapi sastra yang mereka akrabi adalah sastra dalam bahasa-bahasa lokal yang beragam. Adapun tradisi sastra berbahasa lokal yang terdekat dengan tradisi sastra Indonesia modern tentu tradisi sastra Melayu klasik. Dan tidaklah keliru jika disebutkan bahwa tradisi sastra Indonesia hari ini merupakan kelanjutan dari tradisi sastra Melayu yang telah eksis sejak beratus-ratus tahun lampau.
Jika kita periksa sejarah tradisi sastra Melayu ini sejauh yang telah tercatat, maka akan bersua juga kita dengan penyair besar yang punya peran penting bagi eksistensi bahasa Melayu selama berabad-abad. Ia adalah Hamzah Fansuri. Diperkirakan hidup pada sekitar paruh akhir abad ke-16 (kira-kira seangkatan Shakespeare), Hamzah Fansuri adalah penyair yang juga dikenal luas sebagai ulama besar di Kesultanan Aceh Darussalam. Sebagai tokoh sufi Hamzah Fansuri banyak menulis puisi-puisi bertema mistik Islam, dan sering dikaitkan dengan ulama sufi cum penyair Andalusia, Ibnu ‘Arabi.
Ketokohan dan kedudukannya di kesultanan yang sedang jaya-jayanya masa itu membuat puisi-puisi Hamzah Fansuri sangat populer dan tersebar luas sampai ke negeri-negeri yang jauh di Nusantara. Inilah momen sangat penting dalam sejarah alam pikiran bangsa Melayu-Indonesia. Hamzah Fansuri telah mendirikan tonggak tradisi sastra Melayu klasik yang segera dikukuhkan oleh pujangga-pujangga generasi selanjutnya, seperti Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala).
Meski gagasan mistiknya segera diredupkan oleh Nuruddin Ar-Raniri, tradisi menulis dalam bahasa Melayu yang dirintis Hamzah Fansuri tetap hidup dan terus berkembang. Pada abad ke-19 tradisi ini melahirkan penyair penting lainnya, yakni Raja Ali Haji (1808‒1873). Ia dikenal luas sebagai penggubah Gurindam Dua Belas dan perumus pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu.
Pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Melayu yang disepakati sebagai bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu versi Raja Ali Haji yang berakar jauh pada Hamzah Fansuri. Pada gilirannya, bahasa Melayu ini dikembangkan lagi oleh Amir Hamzah (1911‒1946), Raja Penyair Pujangga Baru.
Namun, puisi-puisi Hamzah Fansuri, Raja Ali Haji, dan Amir Hamzah hanyalah representasi dari sebagian bahasa Melayu saja, yakni bahasa Melayu tinggi. Kenyataannya, di masyarakat luas juga eksis bahasa Melayu rendah/pasar. Dalam kondisi seperti ini kemudian hadir Chairil Anwar (1922‒1949) dengan puisi-puisinya yang menyegarkan bahasa Melayu/Indonesia. Di tangan Chairil keindahan bahasa tak lagi melulu berasal dari bahasa Melayu tinggi yang mendayu-dayu, tapi juga dari bahasa percakapan yang lugas. Maka, tonggak baru bahasa dan sastra Indonesia kembali dipancangkan. Tonggak yang tinggi menjulang, sehingga siapa pun penyair yang lewat kemudian nyaris mustahil tak diliputi bayang-bayangnya. Singkat kata, Chairil yang kelak dikenal sebagai pelopor angkatan ‘45 dan ikut aktif berjuang pada masa-masa revolusi, telah merevolusi pula bahasa Indonesia sebagai alat ucap dan alat pikir bangsa Indonesia.
#
Di mana-mana penyair besar punya pengaruh besar dalam sejarah sastra bangsanya. Ia menginspirasi munculnya pujangga-pujangga besar lainnya, membangun tradisi sastra yang pada gilirannya semakin memengaruhi alam pikiran bangsa tersebut. Alam pikiran Inggris tak terlepas dari tradisi sastra Inggris yang telah melahirkan pujangga-pujangga besar seperti Byron, Orwell, Jane Austen, Virginia Woolf, dan Charlotte Bronte. Tradisi sastra Inggris bertonggak pada kebesaran karya-karya William Shakespeare.
Tak ada karya besar yang tiba-tiba jatuh dari langit, tanpa akar apa-apa dari tradisi tempat ia eksis. Tradisi meneroka kemungkinan-kemungkinan, memuluskan jalan, dan memberi tangga bagi karya-karya kemudian yang hendak berjaya. Tradisi sastra yang mapan merupakan modal besar bagi alam pikiran suatu bangsa.
#
Puisi berkaitan erat dengan bahasa. Kekuatan puisi terletak pada kekuatan bahasa. Penyair dalam menggubah puisi cenderung memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki suatu bahasa untuk mencapai daya pukau dan daya gugah. Karena karakter bahasa satu dan lainnya berbeda-beda, maka potensi kekuatan yang dikandung masing-masingnya juga berbeda-beda. Sudah lazim dimaklumi bahwa puisi tak pernah bisa diterjemahkan secara utuh ke bahasa lain. Selalu ada kualitas bahasa yang hilang atau berkurang dalam terjemahan. Karena itu, sejatinya penyair besar hanya menemukan eksistensinya yang sungguh-sungguh dalam bangsanya sendiri. Berbahagialah bangsa Italia yang memiliki Dante. Berbahagialah bangsa Prancis yang memiliki Hugo dan Baudelaire. Berbahagialah bangsa Rusia yang memiliki Pushkin. Mereka adalah bangsa-bangsa yang telah punya kesempatan mewah untuk menenggak sihir kata-kata dan menyelami pemikiran-pemikiran dan penghayatan-penghayatan indah melalui kerja-kerja besar penyair mereka. Hanya masing-masing mereka saja yang bisa mengalami; bangsa lain hanya sekadar tahu bahwa penyair-penyair mereka hebat, tapi tak mengalami sendiri kehebatan-kehebatan itu.
#
Phillip K. Hitti, dalam bukunya History of the Arabs, menulis, “Tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang menunjukkan apresiasi yang sedemikian besar terhadap ungkapan bernuansa puitis dan sangat tersentuh oleh kata-kata, baik lisan maupun tulisan, selain bangsa Arab.” Puisi adalah identitas yang sangat dibanggakan bangsa Arab sejak jauh sebelum kedatangan Islam. Puisi adalah keterampilan yang dipuja-puja bangsa Arab melebihi apa pun. Maka, banyak orang Arab sejak dulu berlomba-lomba menjadi penyair unggul. Konsekuensinya, bangsa Arab melahirkan tradisi sastra yang luar biasa.
Tradisi ini semakin menjulang dan tak tertandingi ketika Al-Qur’an turun ke bumi melalui bangsa Arab‒bahasa Arab‒pada awal abad ke-7. Sejumlah pakar sastra Arab tidak memasukkan Al-Qur’an ke dalam kategori puisi, tapi mengakuinya lebih dahsyat dari puisi mana pun yang pernah ditulis bangsa Arab. Teks Al-Qur’an mengandung bahasa yang puitis, tapi secara keseluruhan ia lebih agung dari puisi. Terlepas dari masalah pengkategorian tersebut, Al-Qur’an tak terbantahkan punya pengaruh besar dalam pembaharuan puitika sastra Arab, bahasa Arab, dan alam pikiran bangsa Arab secara umum.
Adonis menulis dalam Pengantar Puitika Arab bahwa Al-Qur’an merupakan “dasar bagi dinamisme kultural yang inovatif dalam masyarakat Arab-Islam, sumber air sekaligus porosnya”. Adonis menegaskan juga bahwa “modernitas dalam puisi Arab secara khusus, dan dalam bahasa tulisan secara umum, berakar dari Al-Qur’an”. Di sini dapat dibayangkan bahwa penyair-penyair besar Arab yang hidup selepas abad ke-7, seperti Al-Mutanabbi, Abu Nuwas, Al-Niffari, Al-Ma’arri, tak mungkin lepas dari pengaruh kuat Al-Qur’an.
Gelora sastra yang dipicu keajaiban Al-Qur’an ini pada gilirannya ikut mempengaruhi dinamika kerja-kerja intelektual di dunia Arab, membayangi jenius-jenius Arab yang kemudian menghadirkan era keemasan yang gilang-gemilang pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Tradisi raksasa ini lalu berlanjut melahirkan penyair-penyair besar lainnya, seperti Kahlil Gibran, Al-Jawahiri, Nizar Qabbani, Mahmoud Darwish, dan Adonis.
Berbahagialah bangsa Arab yang memiliki tradisi sastra yang luar biasa.
#
Karena puisi berhubungan sangat intim dengan bahasa, puisi sejatinya berperan besar dalam pembentukan kesadaran berbahasa suatu bangsa. Karena bahasa adalah alat bagi manusia untuk berpikir, maka kesadaran berbahasa berarti pula kesadaran berpikir. Kesadaran berpikir ini sangat krusial bagi peradaban manusia. Kesadaran berpikir merupakan kunci bagi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan adalah tiang utama bagi peradaban besar.
Dalam buku Sejarah Filsafat Barat bagian “Lahirnya Peradaban Yunani”, Bertrand Russel menulis, “Syair-syair Homerus, dalam bentuknya yang sekarang, dibawa ke Athena oleh Peisistratus yang bertakhta (dengan beberapa jeda) dari tahun 560 sampai 527 SM. Sejak saat itu dan seterusnya, generasi muda Athena mempelajari Homerus dengan menghapal, dan ini merupakan bagian terpenting dalam pendidikan mereka.” Jadi, puisi-puisi Homerus punya peran besar dalam membentuk pemikir-pemikir Yunani Kuno yang pada gilirannya sampai pada Sokrates, Plato, Aristoteles, dan Aleksander Agung.
Ini merupakan salah satu contoh bahwa puisi sangat berkaitan erat dengan dunia pemikiran, dan dunia pemikiran berkaitan erat dengan peradaban suatu bangsa. Untuk lebih memperjelas keterkaitan antara puisi dan pemikiran, ada baiknya kita menggunakan semacam analogi.
Kita selalu terkagum-kagum pada orang-orang yang menguasai segala aspek yang menjadi bagian inheren dari profesinya. Misalnya, pemburu andal yang sangat terampil menggunakan berbagai perkakas untuk menangkap binatang-binatang buruannya. Ia tidak hanya paham karakter-karakter binatang, tapi juga tahu senjata mana yang paling ampuh untuk menaklukkan buruannya pada kondisi-kondisi tertentu. Ia lihai memasang jerat, tahu bagaimana dan di mana sebaiknya menaruh umpan, dan tahu kapan harus menunggu dan kapan harus mengambil tindakan. Ia tahu bagaimana membuat pisaunya bertambah tajam. Ia mungkin juga menciptakan senjata khusus yang lebih mematikan untuk menaklukkan hewan-hewan yang lebih tangguh. Singkatnya, ia tahu berbagai macam seluk-beluk alat yang ia gunakan untuk berburu. Ia mencintai pekerjaannya, dan ia menemukan kenikmatan yang khas dari memainkan alat-alat yang ia gunakan dalam berburu.
Dengan cara yang sama, kita juga bisa membayangkan ahli pikir seperti itu. Ahli pikir memburu ilmu pengetahuan, memburu hikmah, memburu pemahaman-pemahaman dan penghayatan-penghayatan. Ia boleh saja disebut dengan status macam-macam: filsuf, pujangga, peneliti, ilmuwan, profesor, sarjana, intelektual, cendekiawan, pemimpin, dan seterusnya. Namun, mereka semua sama-sama menggunakan bahasa sebagai alat kerja. Dengan bahasa, mereka menjaring buruan mereka: ilmu pengetahuan, hikmah, pemahaman, penghayatan.
Sebagaimana pemburu yang baik sangat menguasai perkakas-perkakasnya dengan baik, ahli pikir yang baik tentu harus menguasai pula perkakasnya dengan baik, yakni bahasa. Ahli pikir yang baik pasti punya kesadaran dan kepekaan berbahasa yang sangat baik. Ia paham betul sifat-sifat bahasa dan menghayati betul apa-apa saja yang dapat diperbuat dengan bahasa. Kesadaran dan kepekaan berbahasa yang baik pada gilirannya akan cenderung membawa seseorang pada kecintaan pada puisi‒begitu pun sebaliknya. Dengan kata lain, ahli pikir merupakan orang-orang yang mudah akrab dengan puisi. Maka, tak mengherankan jika kita membaca dalam biografi-biografi pemikir besar bahwa mereka sangat gandrung dengan puisi. Sebagian dari mereka hanya membaca puisi (misalnya, pemikiran revolusioner Fidel Castro berutang langsung pada puisi-puisi Jose Marti), sebagian lain mengkaji/memikirkan dengan serius hal-ihwal puisi (misalnya, Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Heidegger, Derrida), dan sebagian lain menulis puisi dengan serius.
Karl Marx muda adalah penulis puisi yang penuh gairah, bahkan ia menulis banyak puisi untuk istrinya. Nietzsche adalah filsuf besar yang berpuisi dalam berfilsafat, atau berfilsafat dalam berpuisi‒puisinya adalah filsafat; filsafatnya adalah puisi. Imam Syafi’i menulis banyak puisi secara serius, menjadikannya dikenal sebagai ulama yang puitis. Ibnu Sina menerbitkan puisi-puisi yang dimaksudkan untuk pengobatan. Omar Khayyam adalah ahli matematika yang popularitasnya lebih banyak berasal dari puisi-puisi rubayatnya. Muhammad Iqbal sama-sama dikenal luas sebagai ulama besar, filsuf besar, dan penyair besar. Stalin muda juga rajin menulis puisi, bahkan beberapa di antara puisinya sempat terbit secara anonim di jurnal sastra ternama di Rusia. Mao Zedong menulis banyak puisi sepanjang hidupnya, termasuk selama ia memimpin revolusi Republik Cina, dan dipublikasikan menjadi satu kitab puisi yang dalam terjemahan bahasa Inggris berjudul The Poems of Mao Zedong. Pemimpin revolusi Republik Islam Iran, Ayatullah Khomeini juga punya dua buku koleksi puisi mistik yang dalam terjemahan bahasa Inggris berjudul The Wine of Love dan Jug of Love. Bapak Bangsa sekaligus pemimpin revolusi Filipina, Jose Rizal juga menulis banyak puisi. Bahkan, menjelang hari eksekusi matinya ia menulis sebuah puisi legendaris berjudul Mi Ultimo Adios (Selamat Tinggalku Penghabisan), membuat kisah hidupnya ditutup dengan kematian yang puitis.
Ini semua merupakan sebagian contoh belaka bahwa ahli-ahli pikir pada dasarnya sangat akrab dengan puisi. Mereka punya kesadaran dan kepekaan berbahasa yang sangat baik, sementara puisi merupakan mahkota bahasa‒puncak penggunaan bahasa.
#
Dalam peradaban Eropa modern, Jerman lazim dikenal sebagai Negeri Para Penyair dan Pemikir (Das Land der Dichter und Denker). Dari julukan itu saja kita bisa melihat dengan jelas bahwa antara penyair dan pemikir/filsuf terjalin hubungan erat laksana dua saudara kandung yang berasal dari satu keluarga/rumah. Di Jerman, kehadiran penyair dan filsuf sudah seperti barisan panjang dalam sejarah pemikiran Barat. Jerman adalah pabrik penghasil jenius-jenius yang dari masa ke masa terus mencengangkan dunia. Karena itulah, barangkali, Adolf Hitler pernah percaya bahwa bangsa Jerman adalah bangsa paling unggul di muka bumi, dan sudah semestinya pula bahwa seluruh umat manusia menjadi tunduk pada mereka.
Tradisi pemikiran Jerman bisa dipandang mengalami kegemilangan awal pada sosok Martin Luther (1483‒1546). Dialah yang mula-mula mengguncang alam pikiran Jerman lewat protes radikalnya yang menyulut Reformasi, lalu memunculkan Kristen Protestan. Dengan melepaskan diri dari otoritas Gereja Katolik Roma, Martin Luther menyebarkan ajaran Kristen dengan cara baru: menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman. Inilah momentum penting bagi perkembangan bahasa Jerman sebagai bahasa agama. Seperti kitab suci di mana-mana, terjemahan Luther terhadap Alkitab juga ditulis dengan bahasa yang sastrawi. Terjemahan Luther inilah salah satu inspirasi besar bagi kelahiran karya-karya sastra hebat Jerman pada generasi kemudian.
Johann Wolfgang von Goethe (1749‒1832) adalah penyair/pemikir Jerman yang tak lepas dari pengaruh besar Martin Luther, dan kemudian juga menjadi inspirasi utama bagi banyak penyair/pemikir Jerman selanjutnya. Goethe adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam pemikiran abad ke-19, dan dipuja-puja bangsa Jerman secara masif. Dalam hal ini, Goethe tidak saja memainkan peranan besar dalam kejayaan sastra Jerman bertajuk Sturm und Drang, tapi juga sangat berperan bagi kemunculan zaman atomik yang melibatkan fisikawan-fisikawan mentereng, seperti Hermann von Helmholtz, James Maxwell, Heinrich Hertz, Max Planck, hingga Albert Einstein. Goethe adalah penyair besar Jerman, pengembang bahasa Jerman yang signifikan, dan ia menjadi tonggak penting bagi peradaban Jerman modern, baik di bidang sastra, filsafat, maupun sains.
#
Dengan ramainya penyair dan pemikir Jerman dari masa ke masa, tentu ada faktor-faktor penting dalam budaya/peradaban Jerman yang menjadi pendukung bagi kemunculan fenomena tersebut. Eric Weiner dalam buku The Geography of Genius mencoba mencari tahunya, dan menemukan suatu jawaban menarik: selain karena “musim dingin yang muram dan watak yang serius”, kemunculan filsuf-filsuf Jerman yang melimpah, utamanya, adalah karena bahasa Jerman itu sendiri. “Bahasa tersebut meminjamkan dirinya pada pemikiran filosofis.” Apa hubungan bahasa Jerman dengan laku filosofis? Gampangnya, bahasa Jerman itu “luar biasa fleksibel”, sehingga “bangsa Jerman terus-menerus menciptakan kata. Bahasa mereka dirancang untuk menciptakan kata.”
Keluwesan bahasa paralel dengan keluwesan pikiran untuk terus berkreasi dan mengembangkan pengetahuan. Realitas begitu kompleks, maka bahasa yang kaku serta miskin kosakata cenderung gagal mengartikulasikan kompleksitas tersebut dengan cermat. Begitu pun sebaliknya. Kata Weiner lagi, “bahasa bukan hanya merefleksikan pemikiran, tetapi membentuknya.”
Puisi, sebagai wujud kreativitas dan ekspresi bagi kompleksitas makna, merupakan katalisator bagi peluwesan suatu bahasa. Puisi selalu berorientasi pada kesegaran ekspresi dan berpantang pada klise. Puisi adalah manifestasi dari kebebasan bahasa, sementara filsafat adalah manifestasi dari kebebasan pikiran. Hanya pikiran dan bahasa yang bebas yang cenderung mampu secara luwes mengartikulasikan realitas yang kompleks, keos, dan dinamis. Pikiran dan bahasa yang kaku-beku hanya akan merepresentasikan realitas secara picik, sementara kepicikan adalah satu nafas dengan kemandekan (peradaban).
Di banyak kebudayaan dan peradaban, penyair selalu menyumbangkan perkembangan bahasa yang signifikan bagi (alam pikiran) bangsanya. Ribuan kata dan frasa dalam bahasa Inggris hari ini merupakan hasil kreativitas William Shakespeare di masa lampau. Khazanah bahasa Spanyol modern banyak berutang ekspresi pada Miguel de Cervantes. Bahasa Italia modern tak mungkin menjadi seperti sekarang tanpa peran besar karya-karya Dante Alighieri. Bahasa Rusia pun tak terlepas dari pengaruh karya-karya Aleksander Pushkin. Itu baru segelintir penyair besar yang mengembangkan bahasa bangsanya secara individual. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya bahasa suatu bangsa dengan jumlah penyair yang lebih ramai, dengan kreativitas masing-masingnya yang sama cemerlang, dari masa ke masa, seperti bahasa Jerman yang dalam tradisi alam pikiran Jerman dikembangkan oleh Goethe, Schiller, Novalis, Heine, Nietzsche, Rilke, dan Brecht.
#
Sampai di sini dapat dilihat bahwa puisi mempunyai hubungan yang sangat intim dengan bangsa pemiliknya. Tidak sekadar mewakili roh/kesadaran bangsa seperti yang diyakini kaum romantik Eropa pada abad ke-19, puisi pada dasarnya juga punya peran besar bagi pembangunan peradaban bangsa tersebut, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan alam pikiran bangsa tersebut. Puisi tidak hanya ikut menyatukan suatu bangsa, entah melalui pengembangan bahasa atau manifestasi karakter kolektif, tapi juga ikut memajukan bangsa melalui pembangunan kesadaran dan kepekaan berbahasa bangsa yang bersangkutan. Kesadaran dan kepekaan berbahasa mendekatkan seseorang pada kesadaran berpikir, dan bangsa yang akrab dengan aktivitas berpikir sungguh-sungguh, sejatinya akan menjadi bangsa yang betul-betul peduli dengan kebijaksanaan: kebenaran, kebaikan, keindahan.