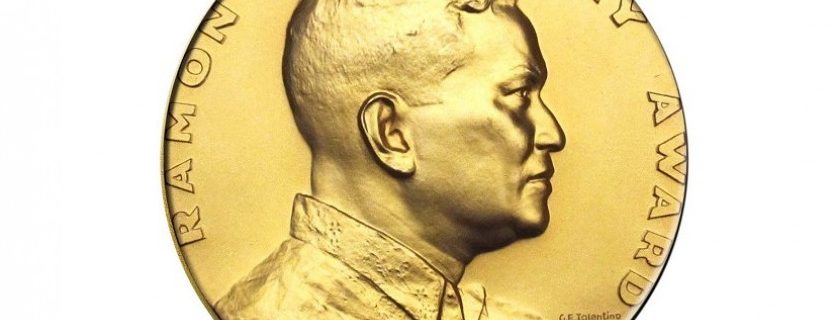Tantangan Konservasi Meurukon
Sebelum maraknya perkembangan media massa (televisi dan radio), teknologi informasi dan komunikasi, internet, dan teknologi hiburan, kegiatan meurukon merupakan salah satu wahana dakwah, pendidikan keagamaan sekaligus sekaligus sarana hiburan rakyat. Seni pertunjukan ini mempertontonkan tanya-jawab (debat) masalah keagamaan Islam oleh dua kelompok atau lebih menggunakan bahasa puitis (syair) yang digubah dalam bait-bait yang disebut rukon. …