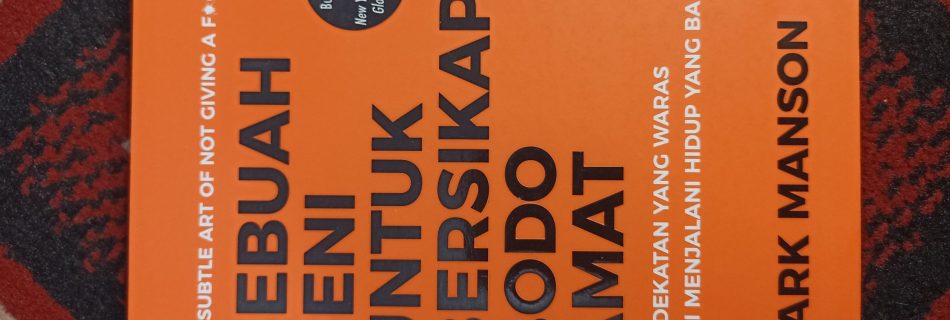Epiktetos di Hadapan Hidup yang Keos
Jika kau ingin Tuhan jadi menyenangkan bagimu, pandanglah Dia dengan mata orang-orang yang mencintai-Nya. –Jalaluddin Rumi Dalam pleidoinya di hadapan seluruh warga Athena, Sokrates berkata kepada orang-orang yang ingin membuatnya dijatuhi hukuman mati, “Ketahuilah, jika kalian membunuhku, kalian tak akan menyakiti siapa-siapa kecuali diri kalian sendiri.” Pernyataannya terkesan retorik belaka, tapi sebenarnya Sokrates tidak sedang …